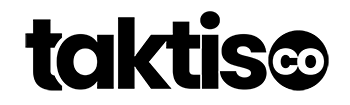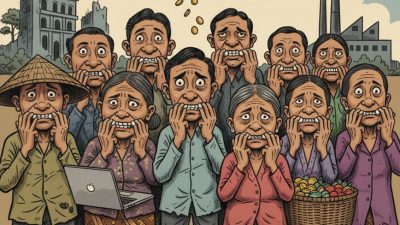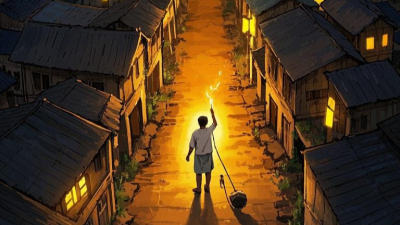Pemerintah patut diapresiasi atas upaya meningkatkan alokasi alat mesin pertanian (alsintan) modern, seperti combine harvester dan power thresher, untuk menyambut panen raya pasca Lebaran 2025.
Namun, langkah ini juga perlu dikritisi secara mendalam, terutama terkait efektivitas penyaluran, kesiapan petani, dan dampak lingkungan. Peningkatan dari 1.400 unit pada 2024 menjadi 5.399 unit di 2025 terkesan ambisius, tetapi tanpa strategi pendampingan yang matang, program ini berisiko menjadi “proyek mercusuar” yang minim manfaat riil bagi petani kecil.
Data Kementerian Pertanian (2024) menunjukkan 70% alsintan tahun sebelumnya terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, sementara wilayah seperti Nusa Tenggara dan Papua hanya mendapat 10%.
Jika pola serupa terulang, petani di daerah tertinggal tetap tertinggal. Padahal, laporan Bank Dunia (2023) mencatat 60% petani Indonesia adalah kecil dengan lahan di bawah 0,5 hektare, yang kesulitan mengakses mesin besar.
Alih-alih hanya menambah jumlah, pemerintah perlu memastikan distribusi merata dan memprioritaskan koperasi tani sebagai penerima utama.
Pengalaman tahun 2020-2023 membuktikan bahwa banyak alsintan terbengkalai karena petani tidak mampu mengoperasikan atau memperbaikinya (Kementan, 2020). FAO (2021) menekankan bahwa adopsi teknologi pertanian wajib disertai capacity building.
Sayangnya, anggaran pelatihan petani Indonesia masih di bawah 5% dari total anggaran sektor pertanian (BPS, 2023). Tanpa pelatihan berkala dan pendampingan teknis, alsintan modern hanya akan menjadi “besi tua” di gudang desa.
Combine harvester dan power thresher berbahan bakar fosil berpotensi meningkatkan emisi karbon dan memperparah kerusakan tanah akibat over-mechanization. Laporan IPCC (2022) menyebut praktik pertanian industrial skala besar sebagai kontributor 12% emisi global.
Pemerintah seharusnya mengintegrasikan alsintan dengan teknologi ramah lingkungan, seperti mesin bertenaga surya atau biogas, serta mendorong praktik pertanian regeneratif.
Meski alsintan dialokasikan, akses petani terhadap alat ini masih terhambat prosedur administrasi yang rumit. Laporan Ombudsman RI (2024) menemukan bahwa syarat pengajuan bantuan alsintan melibatkan 7-10 tahap verifikasi, termasuk rekomendasi dari kepala desa hingga dinas provinsi. Proses ini menyulitkan petani kecil yang minim literasi birokrasi.
Selain itu, meski alsintan disalurkan ke kelompok tani atau koperasi, biaya sewa peralatan seperti traktor roda empat dan combine harvester tetap mahal, mencapai Rp500.000–Rp1 juta per hektare (SPI, 2023). Padahal, rata-rata pendapatan petani padi hanya Rp2,4 juta per musim (BPS, 2023).
Mahalnya biaya sewa membuat petani miskin kembali mengandalkan tenaga manual, sehingga tujuan efisiensi panen tidak tercapai.
Kementan perlu memperkuat infrastruktur pascapanen, seperti gudang dingin dan pasar digital, untuk mengurangi food loss yang mencapai 23% per tahun (Bank Dunia, 2023).
Selain itu, kenaikan BBM dan kelangkaan pupuk tetap menjadi beban utama petani. Alokasi anggaran untuk alsintan harus seimbang dengan subsidi input pertanian dan perlindungan harga komoditas.
Pada akhirnya, modernisasi pertanian tidak boleh sekadar mengejar angka. Pemerintah harus mengedepankan pendekatan holistik: pemerataan akses, pemberdayaan petani, dan keberlanjutan ekologis.
Persoalan birokrasi yang berbelit dan mahalnya biaya operasional alsintan harus diatasi dengan simplifikasi prosedur dan regulasi tarif sewa yang terjangkau. Jika tidak, program alsintan hanya akan memperlebar jurang antara petani besar dan kecil, serta mengorbankan kedaulatan pangan jangka panjang.**
Dadan K Ramdan
Penulis adalah Pegiat Pangan tinggal di Purwakarta Jawa Barat.