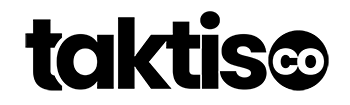Kualitas pekerjaan infrastruktur hanya dapat terjamin apabila proses pengawasan dan pengendaliannya dilakukan secara terukur, transparan, dan konsisten. Namun, di lapangan, lemahnya kontrol dan dominasi “faktor X” dalam proses pemenangan tender proyek justru menjadi patologi yang merusak tatanan sistem pengadaan barang dan jasa.
Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta, Agus M. Yasin, mengatakan bahwa fenomena “nakalnya pemborong” sepertinya bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan akibat dari sistem tender yang tidak steril dari kepentingan.
“Ketika pemenang proyek ditentukan bukan oleh kompetensi dan kelayakan teknis, melainkan oleh kedekatan, kompromi, atau bahkan imbalan tertentu, maka kualitas pekerjaan di lapangan akan menjadi korban,” kata Kang Agus, Jumat, 17 Oktober 2025.
Secara kausalitas, faktor X dalam tender proyek telah menjadi penyakit laten dan seperti “sustainable legacy” yang sulit terhapuskan. Pekerjaan infrastruktur yang tidak sesuai spesifikasi teknis bukan hanya menurunkan kualitas fisik bangunan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, dan fiskal. Beberapa dampak yang muncul antara lain:
– Kerugian keuangan negara/daerah akibat pengurangan volume atau penggunaan material di bawah standar kontrak.
– Potensi tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
– Sanksi administrasi dan pencantuman daftar hitam (blacklist) bagi penyedia jasa, konsultan pengawas, maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) yang lalai.
– Risiko sosial dan keselamatan publik, seperti kerusakan jalan, jembatan ambruk, atau bangunan publik yang gagal fungsi.
Menurut Kang Agus, kegagalan bangunan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga indikasi adanya pelanggaran hukum dan lemahnya integritas pengawasan. Jika ditemukan penyimpangan dan penyelewengan dalam proyek infrastruktur, tanggung jawab hukum tidak berhenti pada pemborong saja, melainkan dapat melibatkan berbagai pihak sesuai perannya:
1. Penyedia/Pemborong (Kontraktor): Dapat dijerat dengan pasal penggelapan, penipuan, atau tindak pidana korupsi apabila terbukti melakukan manipulasi volume, spesifikasi, atau laporan fiktif. Serta dapat dikenai sanksi administratif dan masuk daftar hitam (blacklist) oleh LKPP.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Bertanggung jawab atas kesesuaian kontrak dan realisasi pekerjaan. Dapat dijerat pasal penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU Tipikor) jika membiarkan atau menyetujui pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
3. Konsultan Pengawas: Dapat dikenai sanksi hukum jika terbukti lalai atau sengaja tidak melaporkan ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak. Dan bisa kehilangan izin usaha jasa konstruksi serta dicabut dari daftar penyedia.
4. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): Bertanggung jawab atas validitas dokumen dan persetujuan pencairan dana. Dapat dikenai delik tanggung jawab jabatan apabila menyetujui laporan kemajuan pekerjaan yang tidak benar.
5. Pihak Ketiga yang Terlibat (Broker, Konsultan Rekayasa, atau Oknum Aparat): Jika terbukti menerima imbalan atau memfasilitasi pemenangan tender tertentu, dapat dijerat pasal gratifikasi, suap, atau turut serta dalam tindak pidana korupsi (Pasal 55 KUHP jo. UU Tipikor).
Kang Agus mengatakan bahwa reformasi harus dimulai dari pembenahan sistem lelang elektronik (LPSE) agar benar-benar terbuka dan bebas intervensi, serta berbasis kinerja penyedia. Selain itu, pengawasan berbasis data lapangan dan audit teknis independen perlu diperkuat agar setiap deviasi mutu dapat segera diidentifikasi.
“Tanpa pengawasan yang terukur dan akuntabel, proyek infrastruktur mudah berubah menjadi arena kompromi antara kepentingan politik, ekonomi, dan bisnis. Kesimpulannya, kualitas infrastruktur publik adalah cermin tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Kang Agus.
Selama faktor X masih memengaruhi proses tender dan pengawasan berjalan setengah hati, maka proyek yang dibiayai uang rakyat hanya akan melahirkan bangunan rapuh, baik secara fisik, moral, maupun hukum.